Minggu malam, 28 Desember 2025. Hari itu Gereja merayakan Pesta Keluarga Kudus. Jam di dinding menunjukkan pukul 21.34 WIB ketika sebuah pesan singkat muncul di layar ponsel: “Romo Mudji sampun seda.”
Aku terdiam. Pangkal lidah terasa kaku dan kering. Tak ada kata yang mampu segera lahir. Seperti ada rasa pilu yang merembes perlahan, dari hati ke seluruh tubuh, menekan dada, dan mengendap dalam keheningan.
Pesan itu benar. Fransiskus Xaverius Mudji Sutrisno, imam Serikat Yesus, berpulang ke rumah Bapa pukul 20.43 WIB di Rumah Sakit Santo Carolus, Jakarta. Serangan jantung mengakhiri ziarah hidupnya pada usia 71 tahun. Hanya selang setahun setelah ia menggenapi usia hidup manusia menurut Kitab Suci: “Umur kami tujuh puluh tahun, dan jika kuat, delapan puluh tahun” (Mazmur 90:10).
Apa yang bisa kukatakan tentang seorang seperti Romo Mudji?
Gereja Katolik dan bangsa Indonesia kehilangan lebih dari sekadar seorang imam. Mereka kehilangan seorang filsuf, guru, budayawan, penulis, seniman, dan—yang sering luput disebut—seorang peziarah iman yang setia bergulat dengan kenyataan manusia. Sosok yang tidak pernah memisahkan iman dari kehidupan, doa dari kebudayaan, dan Gereja dari realitas sosial-politik bangsanya.
Romo Mudji adalah samudera pemikiran dan lelaku yang sangat Katolik—dalam arti yang paling mendalam dan luas: universal. Dibandingkan dirinya, aku hanyalah setetes air hujan yang jatuh ke samudera. Dan apa jadinya bila setetes air hujan itu mencoba bercerita tentang samudera? Ia hanya bisa mengisahkan pengalamannya sendiri saat menetes dan larut. Sesempit itulah obituari ini harus dipahami.
Aku mengenal Romo Mudji sejak dekade 1980-an, bukan lewat perjumpaan langsung, melainkan melalui tulisan-tulisannya yang tajam dan reflektif. Buku-buku dan artikelnya di media massa memperkenalkanku pada cara berpikir yang tidak simplistis. Ia berbicara tentang agama, budaya, sosial, dan politik tanpa terjebak pada slogan. Ia mengajak pembaca berpikir—bahkan ketika itu terasa tidak nyaman.
Belakangan, suaranya juga hadir lewat media elektronik dan media sosial. Namun, baik dalam tulisan maupun lisan, ada satu benang merah yang selalu terasa: kejujuran intelektual dan keberanian moral. Ia tidak sedang mencari aman. Ia tidak pula sibuk membangun citra. Ia lebih memilih setia pada kebenaran yang diyakininya, meski itu berarti berdiri di ruang yang sunyi.
Sebagai pengagum, harus kuakui bahwa terlalu sedikit yang mampu kutangkap dari lautan pemikiran dan lelakunya. Kendalanya bukan pada Romo Mudji, melainkan pada diriku sendiri: aku buta filsafat dan teologi. Namun justru di situlah keistimewaannya. Meski berangkat dari filsafat yang dalam dan teologi yang serius, Romo Mudji tidak menara gading. Ia berbicara dengan bahasa yang membumi, dengan metafora kebudayaan, seni, dan pengalaman hidup sehari-hari.
Ia adalah imam yang percaya bahwa iman tidak boleh tercerabut dari konteks. Bahwa Gereja tidak hidup di ruang steril, melainkan di tengah luka, konflik, dan dinamika masyarakat. Karena itu, ia berani bersuara ketika kemanusiaan terancam, ketika keadilan diselewengkan, dan ketika agama diperalat untuk kepentingan sempit.
Dalam dirinya, iman bukan dogma beku, melainkan proses ziarah yang terus bergerak. Ia tidak takut pada pertanyaan. Ia tidak alergi pada keraguan. Justru di sanalah iman diuji dan dimurnikan. Sikap ini membuat Romo Mudji dicintai sekaligus—tak jarang—dipersoalkan. Namun ia tampaknya telah berdamai dengan konsekuensi itu.
Kepergiannya pada Hari Pesta Keluarga Kudus terasa simbolis. Seolah ia diingatkan kembali pada pusat imannya: Allah yang menjelma dalam keluarga manusia, dalam keseharian yang rapuh, sederhana, dan tidak selalu ideal. Romo Mudji sepanjang hidupnya memang setia pada yang manusiawi. Ia tidak mengidealkan manusia, tetapi juga tidak menyerah pada sinisme.
Kini ia telah pulang. Sugeng kondur, Romo.
Bagi banyak orang, Romo Mudji akan dikenang lewat karya-karya intelektualnya. Bagi sebagian lain, lewat keberaniannya bersuara. Bagiku, ia dikenang sebagai pengingat bahwa berpikir adalah bagian dari iman, dan bahwa iman yang dewasa tidak takut pada kompleksitas hidup.
Samudera itu kini tenang. Setetes air hujan seperti aku hanya bisa bersyukur pernah merasakan percikan kebesaran dan kedalaman itu—meski hanya sesaat.
Semoga Romo Mudji beristirahat dalam damai. Dan semoga kita yang ditinggalkan berani melanjutkan ziarah ini: berpikir jujur, beriman dewasa, dan tetap manusiawi di tengah dunia yang sering kehilangan arah.
Baca Juga : Spaghetti LE SSERAFIM dan Perlawanan atas Kerapian Makna
Cek Juga Artikel Dari Platform : beritajalan
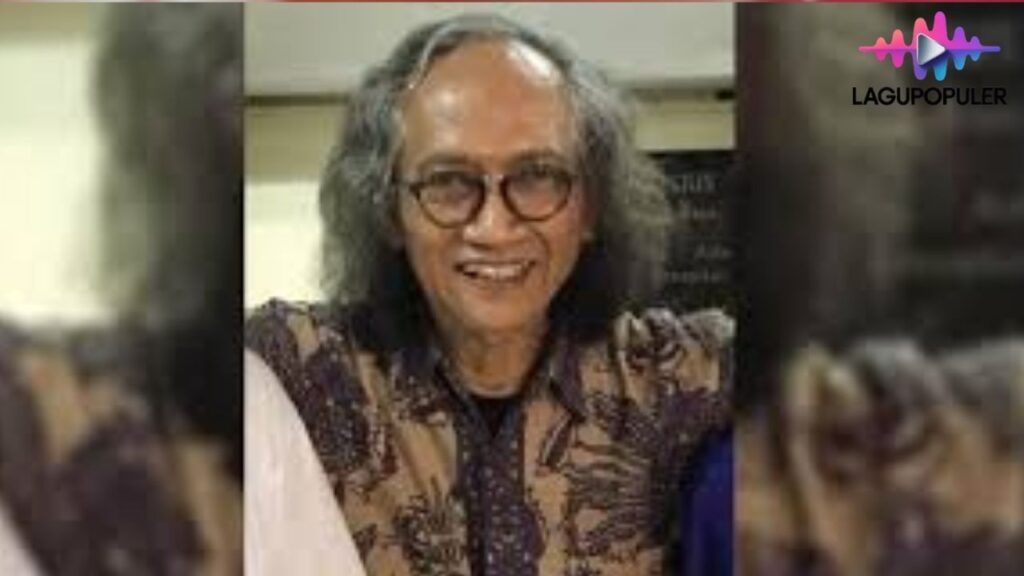





More Stories
Chest Voice: Pengertian, Fungsi, dan Latihan Efektif
Suara Kepala: Apa Itu dan Cara Mencapainya Saat Bernyanyi
Mengenal Teknik Falsetto dalam Olah Vokal